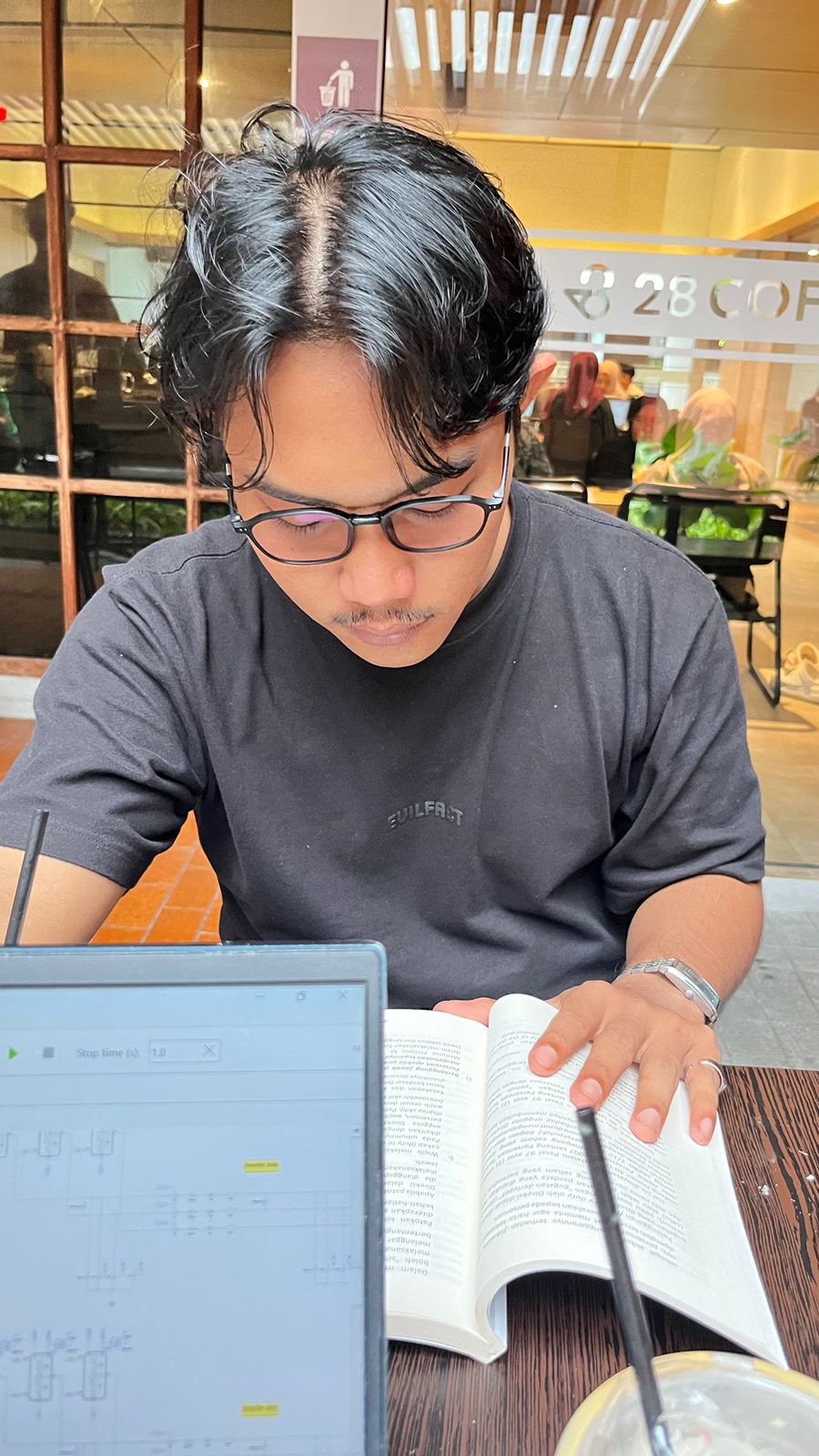Oleh: Awal Ummah S.H
(Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)
Detikdjakarta.com – Menurut data dari dinas perindustrian dan perdagangan Sulawesi Tenggara, dari tahun 2021 hingga tahun 2025 produksi nikel di wilayah sultra mencapai kurang lebih 5,5 juta ton, ini setara dengan 8,6 Miliyar USD. Angka ini menjadi yang terbesar bagi penyumbang ekonomi dari nikel sultra untuk Indonesia, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, menonjol sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia. Dengan cadangan deposit hipotetik mencapai 97,401,593,025.72 ton, dengan angka tersebut Kolaka menjadi wilayah kunci untuk pertambangan nikel.
Namun di balik angka yang fantastis tersebut, lingkungan hidup adalah korban utama yang akan berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Belum lama kemarin pada tanggal 11 Maret 2025, terjadi banjir bandang bercampur lumpur di kecamatan pomalaa, akibat pengoperasian tambang nikel. Kerusakaan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan seperti deforestasi, erosi, dan sedimentasi sungai menyebabkan sungai tidak mampu menahan debit air, dan limpasan air tidak terkendali sehingga menimbulkan banjir, dan merusak pemukiman warga.
Permintaan nikel global yang terus meningkat untuk digunakan sebagai baterai kendaraan listrik, menjadikan nikel sebagai sumber investasi sumber daya alam bagi Indonesia. Potensi nikel yang besar telah membuka banyak lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah dan nasional, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024 tercatat ada 1,7 juta orang yang bekerja di sektor pertambangan. Ini menjadi kondisi dilematis, di satu sisi nikel mampu meningkatkan perekonomian, di sisi lain juga sebagai dalang kerusakan lingkungan dan terancamnya biodiversitas di wilayah sultra.
Meski regulasi lingkungan di Indonesia relatif komprehensif, mulai dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja, hingga PP No. 22 Tahun 2021, fakta empiris justru menunjukkan lemahnya konsistensi penegakan hukum.
Pertentangan norma terlihat ketika tujuan normatif perlindungan lingkungan dikalahkan oleh norma sektoral yang lebih mendorong investasi ekstraktif. Misalnya, prinsip polluter pays yang termuat dalam UU PPLH sering tereduksi karena kewajiban reklamasi atau pemulihan lingkungan ditawar-tawar melalui skema perizinan yang longgar pasca lahirnya UU Cipta Kerja. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara normative design dan law enforcement reality, sehingga dalam hal ini hukum lingkungan cenderung simbolis, dan tidak bersifat operasional.
Dalam konteks ini, mekanisme Corporate Social Responsibility memang digadang sebagai instrumen korektif, namun secara normatif ia hanya diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menekankan kewajiban moral korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas yang hanya berupa penerapan sanksi administrasi.
Pertentangannya jelas bahwa regulasi lingkungan menghendaki pencegahan kerusakan melalui instrumen hukum publik, sedangkan CSR beroperasi dalam ranah hukum privat yang bersifat sukarela dan fleksibel.
Akibatnya, CSR sering diposisikan sebagai substitusi atas kewajiban hukum lingkungan yang semestinya bersifat imperatif. Hal ini menciptakan anomali normatif, perusahaan dapat mengklaim telah menjalankan tanggung jawab lingkungan melalui program CSR, padahal secara faktual mereka masih menjadi penyumbang utama degradasi ekologi.
Solusi normatif dan praktis perlu dirumuskan agar tidak terjadi rule evasion.
Pertama, perlu ada integrasi hukum yang mengikat antara rezim hukum lingkungan dengan regulasi CSR, misalnya melalui klausula wajib bahwa dana CSR sebagian dialokasikan secara terukur untuk rehabilitasi lingkungan di wilayah operasi.
Kedua, perlu diperkuat peran instrumentasi hukum administratif, seperti strict liability dalam kasus pencemaran, sehingga CSR tidak menjadi tameng impunitas bagi korporasi.
Ketiga, masyarakat sipil dan pemerintah daerah harus memperoleh hak akses penuh terhadap informasi pengelolaan CSR (right to know), guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan tidak hanya berhenti pada level deklaratif, tetapi bertransformasi menjadi rezim yang mampu menyinergikan norma hukum publik dengan norma tanggung jawab privat korporasi secara substansial.